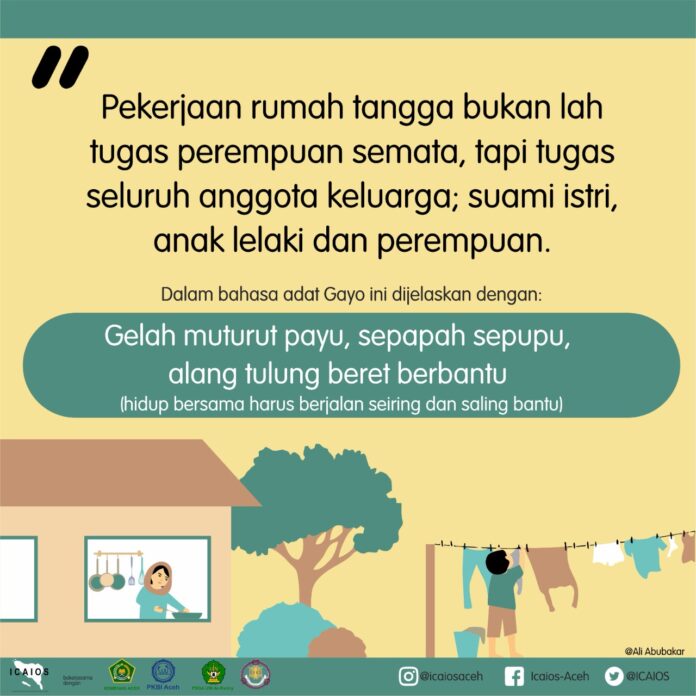COVID-19 dan Keluarga
Saiful Mahdi*
COVID-19 telah mengubah banyak hal. Di tengah wabah yang tentu saja sebuah bencana ini, kita mencatat dan mungkin mengalami sejumlah “hikmah”. Dus, ungkapan “semua ada hikmahnya” makin sering mendapat pijakan empiris.
Bekerja, belajar, dan beribadah di dan dari rumah ikut membawa sejumlah hikmah. Mungkin seperti banyak keluarga lain, kita juga menikmati new normal ini. Menghabiskan sebagian besar waktu di rumah dan bersama keluarga adalah sebuah berkah. Banyak kawan menuliskan betapa keluarga mereka sekarang lebih sering makan bersama, shalat berjama’ah, dan melakukan sejumlah aktivitas bersama lainnya.
Tapi itu di bulan April-Agustus. Saat awal pandemi dan akhir semester menjelang dan selama libur sekolah. Walaupun tak bisa bepergian seperti di masa libur sebelumnya, kita masih bisa menikmati kebersamaan bersama keluarga.
Kemudian sekolah dimulai pada Agustus-September lalu. Wabah belum mereda. Karena itu, sebagian besar kegiatan belajar masih dilakukan secara online. Dari rumah. Ya, kita masih harus bekerja dan beribadah di dan dari rumah. Anak-anak juga masih di rumah!
Sebuah kenormalan baru yang sebenarnya sudah kita rasakan sejak April lalu. Tapi kali ini terasa lebih berat. Terutama yang dirasakan para ibu yang juga bekerja. Beban ganda sebagai ibu dan karyawan kini ditambah lagi dengan peran “guru” untuk anak-anaknya. Dari double burden menjadi triple burden.
Sebagian mungkin kembali menyalahkan perempuan yang bekerja. Jadi sebaiknya ibu yang selama ini bekerja berhenti dari pekerjaannya? Kembali fokus pada pekerjaannya sebagai istri dan ibu di rumah saja? Tapi toh selama ini mereka sudah bekerja bukan?
Pekerjaan rumah tangga
Salah satu kenangan indah saya tentang almarhum Abu (bapak) adalah sayur bayam yang dimasaknya sangat enak. Terasa berbeda enaknya dari sayur bayam masakan Ummi, ibu saya. Ya, bapak saya bisa memasak. Ibu saya lebih jago lagi.
Mungkin karena banyak keluarga dan orang kampung saya yang membuka warung nasi di berbagai kota di Aceh sampai Medan dan Jakarta, keahlian memasak cukup merata di kalangan perempuan maupun laki-laki. Memasak itu bukan tugas perempuan semata.
Anak-anak di masa kecil saya belajar mengaji pertama dari bapak atau ibunya. Setelah punya dasar yang cukup baik, baru kemudian anak laki-laki melanjutkan ke teungku di meunasah. Anak perempuan melanjutkan ke teungku inong atau teungku ibu. Di rumah mereka tetap bisa belajar dari mak atau bapaknya.
Sebagai anak lelaki tertua, saya biasa membantu ibu mencuci piring dan mencuci baju sendiri dan anggota keluarga yang lain. Mungkin karena terbiasa, saat ikut kegiatan Pramuka keahlian dan kecepatan mencuci piring sampai dikenali oleh kakak pembina. Sampai-sampai saya diminta memimpin beberapa anggota regu pramuka menjadi pencuci piring saat pernikahan si kakak pembina itu. Dan kami melakukannya dengan penuh kebanggaan dan semangat. Khas anak pramuka.
Jadi kapan dan mengapa pekerjaan rumah dianggap tugasnya perempuan?
Menurut bacaan dan diskusi tim peneliti ICAIOS dalam Kajian dan Rekonstruksi Keluarga dan Relasi Kuasa di Aceh, domestifikasi peran perempuan tidak selalu berasal dari budaya lokal yang seringkali dianggap lebih patriarki. Tidak juga karena pengaruh Islam sebagai agama yang justru dimulai syiarnya oleh Nabi Muhammad SAW dengan menghilangkan pembunuhan bayi perempuan hidup-hidup oleh bangsa Arab kala itu. Kalaupun agama dipakai untuk membenarkan pembatasan hak perempuan, sebagian hanya karena khilafiyah pada tataran tafsir.
Sistim ekonomi patriarkik
Sebuah masyarakat menjadi patriarki justru lebih karena aturan negara dan sistim ekonomi yang dipraktikkannya. Saat undang-undang atau peraturan pemerintah, misalnya, menyatakan suami sebagai “kepala keluarga” dan istri sebagai “ibu rumah tangga”, tujuannya mungkin baik dan lurus. Namun ketika aturan itu diterapkan oleh birokrat level bawah yang mengelola bantuan sosial (bansos), bisa jadi perempuan kepala keluarga tidak memeroleh bansos yang menjadi haknya karena aturan yang mengatakan penerima bansos harus “kepala keluarga”.
Kapitalisme, apalagi kapitalisme keblinger, menghendaki efisiensi agar pemilik modal bisa melipatgandakan hasil investasi dari modalnya. Karena itu mereka lebih suka pekerja laki-laki ketimbang perempuan yang karena fitrahnya harus meminta cuti haid dan berkemungkinan diajak pindah ke daerah lain sama suaminya. Mungkin karena itu, sampai seleksi dosen di perguruan tinggi pun konon lebih menyukai calon dosen laki-laki. “Ngapain kami terima Anda. Sewaktu-waktu Anda bisa dinikahi oleh laki-laki dari luar daerah. Anda juga tidak bisa kerja lembur sampai malam di tengah laki-laki,” adalah alasan yang sering kita dengar dari para penguasa yang melakukan wawancara pegawai.
Jelas haid yang rutin menghampiri perempuan bukan salah perempuan. Keluarga tak kan ada tanpa haid perempuan. Para pengelola modal pun tidak salah jika ingin memastikan pemilik modal bahagia karena efisiensi pengelolaannya. Tapi pekerja perempuan seharusnya, bila perlu, juga bisa bekerja seefisien bahkan lebih efisien jika lingkungan dibuat memungkinkan. Keperempuanannya bukanlah alasan. Tapi pembagian tugas dan sistim ekonomi itu memang lebih cenderung patriarkik.
Kenapa perempuan tidak bisa bekerja malam di tengah laki-laki kalau memang diperlukan? Karena lingkungannya tidak memungkinkan. Jadi lingkungannya harus dibuat mungkin, misalnya, dengan penerangan yang cukup, privasi dan keselamatan kerja yang terjaga, dan pengaturan shift yang tidak bias gender. Bukan justru kesempatan perempuan yang dipangkas.
Teringat ketika di Amerika para muslimah ingin menggunakan kolam renang milik publik. Bukan mereka harus berenang dengan baju lengkap menutup aurat seperti di sebuah negeri syariat, tapi dengan memastikan seluruh kolam renang isinya perempuan pada ladies/muslimah hours, jam khusus di kolam renang untuk perempuan. Jadi jangan perempuannya yang dibiarkan tidak bisa berenang, sebuah keahlian penting dalam hidup, tapi pengkondisian bisa dilakukan agar perempuan bisa tetap mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki.
Kenapa “pindah ikut suami” dianggap hak asasi yang harus dipenuhi negara, tapi “pindah ikut istri” tidak dikenal? Hanya karena aturan ini, calon pekerja perempuan lebih sulit mendapatkan pekerjaan di lowongan manapun ketimbang laki-laki. Lagi-lagi karena asumsi efisiensi lebih tinggi dimiliki laki-laki bagi pemilik modal. Jadi bias gender itu memang senyawa kapitalisme yang kebablasan.
Karena keluarga dan masyarakat dibentuk dalam sistim ekonomi yang patriarkik, maka keluarga dan masyarakat jadi ikut patriarkhik. Anak laki-laki dianggap sebagai “investasi” yang lebih efisien untuk disekolahkan ketimbang anak perempuan. Dari situ lahirlah ungkapan “anak perempuan kan ujung-ujungnya nanti akan bekisar di dapur, sumur, dan kasur”. Padahal anak jelas bukanlah “investasi”. Pola pikir untung-rugi telah menjadikan kita makhluk ekonomi yang rakus.
Padahal tidak ada ayat Tuhan dan contoh tingkah laku para Nabi yang menunjukkan pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan perempuan. Rasul Allah mencuci bajunya sendiri dan telah bersabda “Sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik pada istrinya.” Menurut para periwayat, Sang Nabi SAW tidak pernah memukul istrinya. (Jadi heran, itu KDRT contoh nabi yang mana?)
Tambahan peran sebagai “guru” bagi anak-anak di rumah selama wabah seharusnya disambut para ibu dan bapak, bahkan anggota keluarga lainnya. Tambahan peran ini akan jadi ladang subur cinta dan kebahagiaan jika dilakukan bersama. Tapi bisa jadi beban bahkan malapetaka jika harus dikerjakan salah satu anggota keluarga saja.
Para ibu yang berteriak akan beban tambahan selama masa pandemi ini patut diduga masih hidup dalam sistim negara dan ekonomi yang patriarki. Bukan sekedar kesalahan suami semata. Para bapak bisa jadi adalah korban sistim yang memang mencengkram seluruh keluarga. Karena baik para bapak dan para ibu masih sibuk harus absensi, misalnya. Bahkan sebagian harus absensi di kantor atau dalam jaringan kantor padahal semuanya seharusnya bisa dilakukan secara online dari rumah saja.
Ada pula para pimpinan yang sedang kejar target penggunaan anggaran dalam sistim negara yang terkadang absurd. Demi capaian anggaran, pertemuan during dan acara di hotel-hotel mulai hidup kembali. Kali ini, selain harus mikirin rapat di kantor, pertemuan di hotel, para orang tua tambah repot karena anaknya masih di rumah. “Penitipan anak” yang namanya sekolah belum buka!
Mari belajar kembali menikmati peran negara yang berkurang dalam hidup kita. Anak-anak kita kembali ke tangan kita dari cengkraman negara lewat sekolah, sebagian full day, yang belum tentu bermutu. Istri dan suami kita lebih banyak di rumah ketimbang harus menghadiri apel dan rapat-rapat yang diisi pidato menjemukan para penguasa lembaga negara yang tidak kompeten. Para mahasiswa bisa belajar dengan gembira, terbebas dari tekanan harus punya pakaian termodis dan gawai terbaru yang dibentuk oleh gaya hidup hedonis, anak kandung kapitalisme yang sesat.
“Semua ada hikmahnya”. Hikmah di sini adalah kebijaksanaan, wisdom. Semoga kita makin bijaksana dalam melihat peran anggota keluarga, terutama peran suami dan anak laki-laki dalam keluarga kita selama masa pandemi ini.
“Pekerjaan rumah tangga bukanlah tugas perempuan semata, tapi tugas seluruh anggota keluarga: suami, istri, anak laki-laki dan perempuan.”
*Dosen Jurusan Statistika Unsyiah, anggota tim peneliti ‘Rekonstruksi Konsep Keluarga dan Relasi Kuasa di Aceh’ ICAIOS. Email: [email protected]